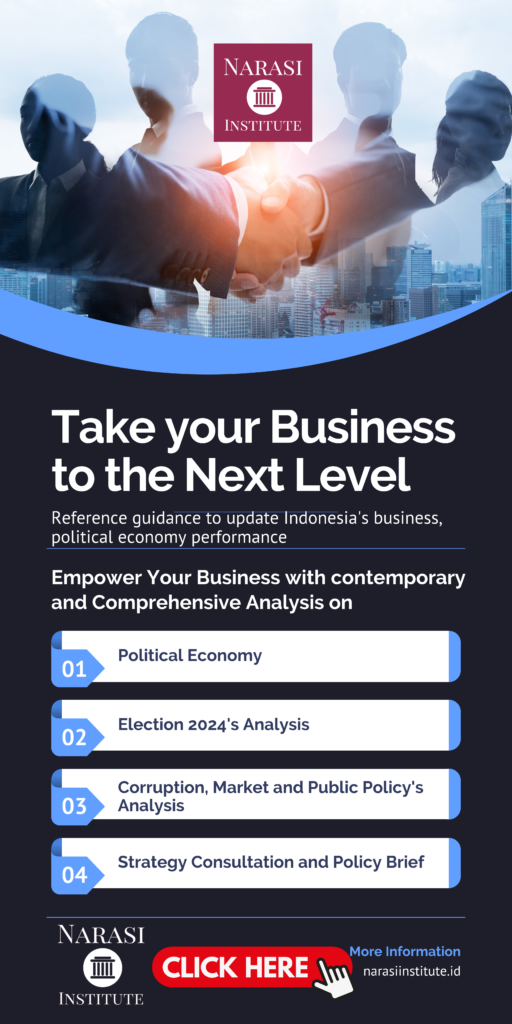DAILYPOST.ID” – Kita hidup di negeri yang ironis. Tak perlu diperdebatkan lagi, negeri ini kaya. Bumi Pertiwi menyimpan kekayaan alam melimpah, dari minyak dan gas hingga emas yang terkubur di perut bumi.
Kaya akan sumber daya energi, tetapi rakyat kecil harus antre berjam-jam untuk sekadar menyalakan api di dapur. Gas melon—yang katanya bersubsidi—kini berubah menjadi barang mewah. Pemerintah berdalih ingin distribusi lebih tertata, lebih tertarget, lebih “adil”. Namun, ironisnya, masyarakat masih menghadapi kelangkaan LPG 3 kg, yang seharusnya tidak terjadi mengingat potensi energi yang ada.
Fakta dari berbagai daerah membuktikan kekacauan ini. Berdasarkan laporan beberapa media, di Jakarta, harga gas 3 kg di pangkalan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara di Gorontalo, warga mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya LPG, harga bisa menyentuh Rp35.000 per tabung. Para ibu rumah tangga kelelahan menunggu giliran, UMKM meratap karena kehilangan bahan bakar usahanya. Bahkan, seorang ibu di Pamulang meninggal dunia setelah antre berjam-jam demi satu tabung gas. Inikah yang disebut “subsidi tepat sasaran”?
Menanggapi situasi ini, pemerintah berencana menertibkan para pengecer gas elpiji 3 kg untuk dijadikan sub pangkalan dengan aplikasi, dengan jumlah mencapai 370.000 pengecer. Namun, pembeli tetap harus menggunakan KTP saat melakukan pembelian. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Achmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menilai bahwa kebijakan tersebut justru mempersulit masyarakat miskin dalam mendapatkan hak mereka. Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada pengawasan distribusi agar subsidi benar-benar tepat sasaran, bukan dengan membatasi atau menyulitkan akses masyarakat. (Tribunnews)
Pemerintah ingin menghapus pengecer karena dianggap menyebabkan distribusi tidak merata. Solusi yang ditawarkan adalah pembelian di pangkalan resmi dengan KTP. Namun, bagaimana dengan mereka yang tinggal jauh dari pangkalan? Bagaimana nasib masyarakat kecil yang bergantung pada warung-warung sebagai sumber LPG mereka? Benarkah solusinya adalah dengan menghapus pengecer?
Negara, yang seharusnya menjadi penjaga distribusi dan penjamin kesejahteraan, justru absen dalam menjalankan perannya. Distribusi energi bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang hak dasar masyarakat untuk hidup layak. Jika negara benar-benar ingin menjamin LPG 3 kg sampai ke tangan yang berhak, maka solusi yang harus diambil bukanlah sekadar melarang pengecer, tetapi membenahi sistem distribusi
Kisah lama terulang kembali
Setiap menjelang momen spesial—Ramadhan, Lebaran, atau hari-hari besar lainnya—harga kebutuhan pokok melonjak, barang-barang menghilang dari pasaran, dan rakyat kembali mengantre panjang dengan wajah penuh harap. Gas melon, sang primadona dapur rakyat, tak luput dari siklus ini. Tahun demi tahun, kelangkaannya menjadi ritual tahunan yang entah sampai kapan akan berakhir.
Mirisnya, ini bukan sekadar insiden sesaat yang bisa dianggap kebetulan. Kenaikan harga dan sulitnya akses terhadap LPG 3 kg sudah seperti pola yang dipahami semua orang, kecuali, tampaknya, oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Lalu, mengapa negara yang katanya kuat justru terlihat begitu lemah dalam memastikan rakyatnya bisa memasak tanpa cemas?
Apakah ini soal ketidaksengajaan? Atau justru ada tangan-tangan tak terlihat yang terus bermain dalam kegelapan, menjadikan gas sebagai komoditas yang lebih menguntungkan jika dibuat langka? Yang jelas, setiap kali rakyat mengeluh, jawabannya selalu sama: “Situasi sedang dikendalikan.” Tapi hingga kapan? Hingga rakyat terbiasa dengan ketidakpastian? Atau hingga mereka tak lagi punya daya untuk bertanya? Menggelikan.
Logika Kapitalisme
Jelaslah, ini bukan sekadar soal distribusi yang tersendat atau kebijakan yang kurang tepat. Ini adalah buah dari sistem yang sejak awal cacat: Kapitalisme, induk dari demokrasi yang diadopsi hari ini. Sistem yang membiarkan segelintir pemilik modal menari di atas penderitaan rakyat, yang mengutamakan keuntungan segelintir orang dibanding kesejahteraan berjuta-juta manusia.
Selama sistem ini bercokol, selama pengelolaan sumber daya alam masih diserahkan pada mekanisme pasar, selama negara hanya berperan sebagai fasilitator bagi korporasi, bukan pengurus rakyat, maka jangan harap kelangkaan ini hanya sekadar episode yang berlalu begitu saja. Ia akan terus berulang, menjadi bagian dari siklus panjang penderitaan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sebuah negara yang berdaulat seharusnya berdiri sebagai benteng bagi rakyatnya, memastikan bahwa setiap kebutuhan dasar, mulai dari energi hingga layanan publik, dapat diakses dengan mudah dan merata. Namun, apa yang kita lihat hari ini justru sebaliknya. Negara lebih sibuk mengatur mekanisme pasar daripada menjamin akses rakyat terhadap hak-haknya. Subsidi dipangkas, distribusi dipersulit, dan pada akhirnya, rakyat kecil yang menanggung dampaknya.
Kelangkaan gas yang terus berulang adalah tanda nyata kegagalan sistem distribusi yang ada. Namun, Islam telah menetapkan aturan tegas dalam mengelola sumber daya alam, termasuk migas, agar kebermanfaatannya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Dalam Islam, kepemilikan umum diatur dengan jelas, sebagaimana sabda Rasulullah, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Gas, sebagai bagian dari sumber energi, termasuk dalam kategori ini—bukan milik individu, bukan pula milik korporasi, tetapi harus dikelola oleh negara demi kepentingan masyarakat.
Efisiensi dalam Islam
Islam telah menetapkan aturan tegas dalam mengelola sumber daya alam, termasuk migas, agar kebermanfaatannya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Dalam Islam, kepemilikan umum diatur dengan jelas, sebagaimana sabda Rasulullah,
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Gas, sebagai bagian dari sumber energi, termasuk dalam kategori ini—bukan milik individu, bukan pula milik korporasi, tetapi harus dikelola oleh negara demi kepentingan masyarakat.
Dalam sistem Islam, negara memiliki otoritas penuh dalam mengelola sumber daya alam tanpa celah bagi swastanisasi atau campur tangan asing. Setiap hasil dari pengelolaan migas akan masuk ke baitulmal, bukan ke kantong-kantong segelintir elite bisnis. Dari sini, negara berperan sebagai raa’in—pengurus umat—yang memastikan bahwa gas sampai ke setiap rumah tangga tanpa hambatan, tanpa permainan harga, tanpa diskriminasi akses. Jika perlu, negara dapat mendistribusikannya secara gratis, atau menetapkan harga yang adil, tanpa mekanisme subsidi yang justru membuka celah bagi mafia bermain di hulu dan hilir.
Distribusi dalam Islam tidak mengenal proses berbelit. Tidak ada pengecer ilegal yang mempermainkan harga, karena sistem sanksi dalam Islam tegas dan memberi efek jera. Para mafia yang mencoba bermain dalam distribusi migas tidak akan sekadar dikenakan denda ringan atau hukuman administratif, melainkan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius, sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang menjaga hak-hak rakyat.
Lebih dari itu, Islam menutup celah ketimpangan dalam konsumsi. Tidak ada pembedaan harga berdasarkan kelas sosial. Semua rakyat mendapatkan haknya dengan adil, tanpa mekanisme yang justru membingungkan dan memicu kecurangan. Di bawah naungan Khilafah, setiap individu sadar bahwa ia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual, bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kepatuhan lahir bukan karena ancaman sanksi semata, tetapi karena dorongan takwa.
Maka, sekali lagi kelangkaan LPG bukanlah sekadar persoalan distribusi, tetapi cerminan dari sebuah sistem yang gagal memahami hakikat kepemilikan umum. Jadi, pertanyaannya bukan lagi sekadar kenapa gas melon langka? tetapi sampai kapan rakyat harus bergantung pada sistem yang tidak berpihak pada mereka?
Sumber: dailypost.id