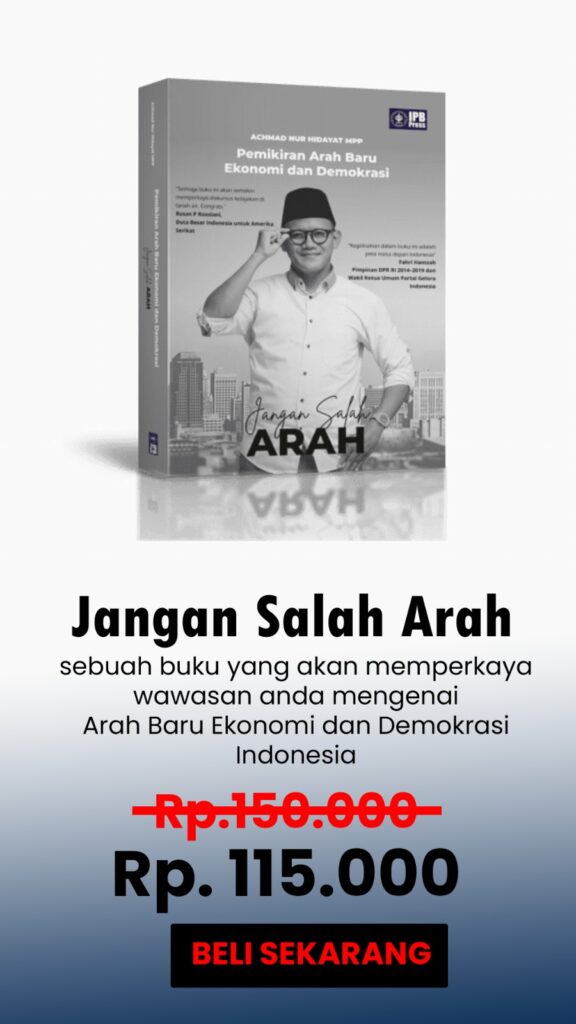Sejarah mencatat bagaimana tanah, sebagai sumber daya yang tak ternilai, sering menjadi pusat konflik antara kepentingan besar dan hak asasi masyarakat lokal. Di satu sisi, ada Palestina, yang selama puluhan tahun mengalami pencaplokan oleh negara tetangganya, Israel. Di sisi lain, jauh di kepulauan Indonesia, Rempang menceritakan kisah serupa, di mana tanah kelahiran masyarakat setempat terancam oleh kepentingan pemerintah dan asing. Kedua daerah ini, meskipun berada di dua belahan dunia yang berbeda, menunjukkan bagaimana tanah yang telah lama menjadi rumah bagi penduduk asli dapat dengan mudah dicaplok oleh kekuatan yang lebih dominan.
Palestina, dengan sejarah panjangnya, telah menjadi saksi bagaimana tanahnya yang subur dicaplok dan dikuasai oleh Israel. Mulai dari pendirian permukiman hingga pembangunan tembok pemisah, rakyat Palestina terus berjuang mempertahankan hak-hak mereka atas tanah yang telah dihuni oleh leluhur mereka selama berabad-abad. Sementara itu, di Rempang, konflik yang mungkin terdengar lebih baru namun tak kalah mendalam, masyarakat setempat menentang upaya relokasi oleh pemerintah. Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka dari ancaman investasi asing yang dapat mengubah total lanskap dan budaya daerah tersebut.
Dalam kedua narasi tersebut, ada benang merah yang menghubungkan Rempang dan Palestina: perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas, warisan, dan hak atas tanah mereka. Kedua daerah ini menjadi cerminan bagaimana kepentingan ekonomi dan politik seringkali mengesampingkan hak asasi manusia. Meskipun konteks dan skala konfliknya berbeda, kisah Rempang dan Palestina mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai hak setiap individu atas tanah dan rumahnya, serta mengingatkan kita untuk selalu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
Rempang: Miniatur Palestina di Indonesia
Rempang, sebuah pulau di kepulauan Indonesia, mungkin tidak sepopuler Palestina dalam sorotan media global. Namun, kisah di balik konflik tanah di Rempang menyerupai narasi tragis yang telah lama terjadi di Palestina. Di Rempang, masyarakat setempat menghadapi ancaman relokasi, di mana tanah kelahiran mereka, yang telah dihuni turun-temurun, berada di ambang perubahan drastis karena kepentingan investasi. Pemerintah, dengan agenda pembangunan dan investasi, tampaknya mengesampingkan suara-suara masyarakat lokal yang berusaha mempertahankan tanah dan rumah mereka.
Mirip dengan apa yang terjadi di Palestina, di mana permukiman Israel terus menerus dibangun di wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari tanah Palestina, Rempang menghadapi dilema serupa. Kedatangan kepentingan asing dan investasi besar-besaran sering kali menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Di Rempang, protes dan penolakan masyarakat terhadap relokasi menjadi bukti nyata dari perjuangan mereka untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka.
Dalam konteks ini, Rempang bisa dilihat sebagai miniatur dari Palestina di Indonesia. Meskipun skala dan konteks geopolitiknya berbeda, esensi konfliknya sama: perjuangan masyarakat lokal melawan pencaplokan tanah oleh kekuatan yang lebih dominan. Kedua daerah ini menjadi saksi bisu bagaimana kepentingan ekonomi dan politik sering mengabaikan hak asasi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kisah Rempang mengingatkan kita untuk selalu berpihak pada keadilan dan hak asasi setiap individu.
Kepentingan Asing: Dari Rempang ke Palestina
Ketika kita mendengar tentang konflik tanah dan relokasi, sering kali ada narasi yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya, yaitu intervensi dan kepentingan asing. Baik di Rempang maupun di Palestina, kepentingan asing memainkan peran kunci dalam mempengaruhi dinamika konflik. Di Rempang, dorongan untuk pembangunan dan investasi, yang sering kali melibatkan pihak asing, menjadi alasan utama di balik upaya relokasi masyarakat. Tanah yang subur dan strategis di Rempang menjadi target utama bagi investor yang melihat potensi keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, di Palestina, intervensi asing memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Mulai dari Mandat Britania yang memfasilitasi migrasi Yahudi ke Palestina, hingga dukungan negara-negara Barat terhadap Israel dalam konflik dengan Palestina. Kepentingan geopolitik dan aliansi strategis seringkali mengaburkan garis antara yang benar dan yang salah, mengorbankan hak-hak dasar rakyat Palestina. Permukiman Israel di wilayah Palestina, yang didukung oleh kebijakan dan bantuan dari negara-negara asing, menjadi simbol dari dominasi asing yang mengabaikan hak asasi manusia.
Dalam kedua kasus tersebut, masyarakat lokal menjadi korban dari ambisi dan kepentingan asing. Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah, rumah, dan identitas mereka di tengah tekanan eksternal. Kepentingan asing, baik dalam bentuk investasi ekonomi di Rempang maupun dukungan politik di Palestina, menunjukkan bagaimana dinamika global dapat mempengaruhi nasib komunitas lokal. Adalah penting bagi kita untuk memahami dan mengakui dampak dari intervensi asing ini, agar kita dapat berdiri bersama masyarakat yang terpinggirkan dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan kedaulatan.
Ketika kita merenungkan kisah Rempang dan Palestina, ada satu kesamaan yang menonjol: ketika hak-hak dasar dan identitas suatu komunitas diinjak-injak demi kepentingan asing atau pihak dominan, perlawanan adalah reaksi alami yang akan muncul. Di Rempang, upaya relokasi yang didorong oleh kepentingan investasi asing telah menimbulkan ketegangan dan protes dari masyarakat setempat. Di Palestina, pendudukan berkelanjutan dan pembangunan permukiman oleh Israel, dengan dukungan dari kekuatan asing, telah memicu konflik dan perlawanan selama beberapa dekade.
Namun, apa yang sering kali terlewatkan dalam diskusi tentang kedua situasi ini adalah potensi mereka untuk menjadi bom waktu konflik yang lebih besar di masa depan. Ketidakpuasan dan rasa dikhianati yang mendalam, yang terakumulasi selama bertahun-tahun atau bahkan berdekade-dekade, dapat meledak sewaktu-waktu. Ini bukan hanya tentang tanah atau properti, tetapi tentang martabat, identitas, dan hak untuk hidup dengan damai di tanah leluhur.
Dengan mengabaikan suara-suara masyarakat asli dan mengejar kepentingan jangka pendek, pemerintah dan kekuatan asing mempertaruhkan stabilitas dan perdamaian jangka panjang. Sebagai masyarakat global, kita harus memahami dan mengakui potensi bahaya ini. Kita harus mendesak pemangku kepentingan untuk memprioritaskan hak-hak masyarakat lokal dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Jika tidak, kita mungkin akan menyaksikan ledakan konflik yang lebih besar, yang akarnya dapat ditelusuri kembali ke ketidakadilan yang terjadi hari ini.
Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP. (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)