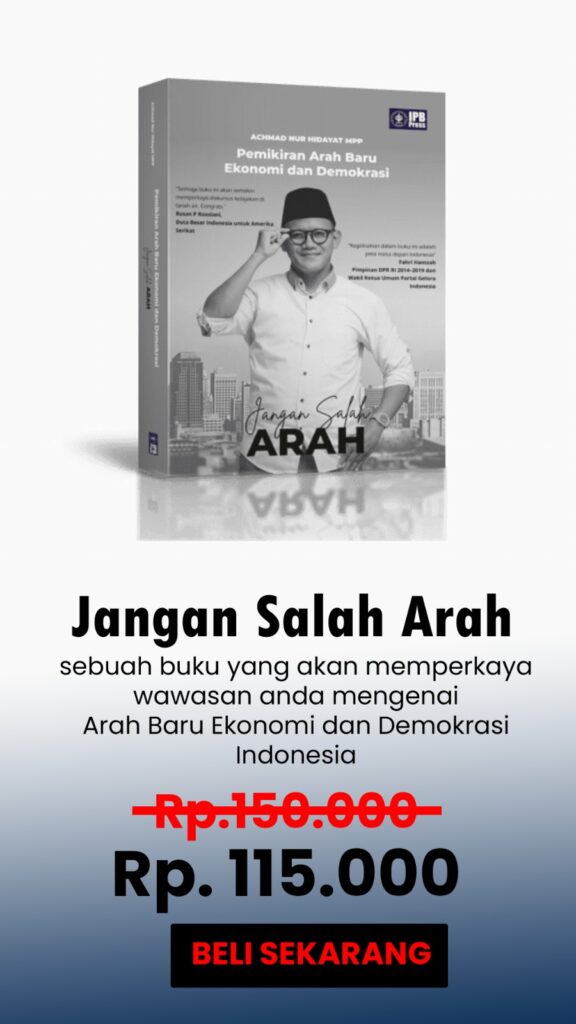Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute
Pembangunan di berbagai belahan dunia seringkali dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa pendekatan inklusif, pembangunan bisa jadi hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu sementara meninggalkan kelompok lainnya. Dalam konteks Pulau Rempang, perempuan Melayu, yang memiliki ikatan mendalam dengan lahan dan lingkungan setempat, tampaknya terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
Sejarah dan tradisi menunjukkan bahwa perempuan Melayu memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan anak, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelestarian budaya. Keterlibatan mereka dalam mempertahankan lahan yang telah dihuni secara turun-temurun mencerminkan bukan hanya perjuangan atas tanah, tetapi juga perjuangan atas hak, kehormatan, dan warisan budaya.
Pembangunan yang melangkahi peran dan aspirasi perempuan Melayu ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga mengabaikan sumbangsih dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Dalam jangka panjang, ini bisa berdampak pada ketidakberlanjutan pembangunan karena mengabaikan nilai-nilai budaya dan ekologi yang telah dijaga oleh perempuan Melayu selama generasi. Oleh karena itu, menghargai dan melibatkan perempuan dalam setiap tahap proses pembangunan adalah esensial untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kerugian Generasi Muda Akibat Dislokasi
Generasi muda seringkali menjadi pihak yang paling terpengaruh ketika terjadi perubahan drastis dalam lingkungan mereka, seperti dislokasi akibat pembangunan. Pada kasus Pulau Rempang, dislokasi tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga berdampak pada warisan kultural, pendidikan, dan peluang ekonomi yang selama ini tersedia bagi generasi muda di sana.
Ketika generasi muda dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka, mereka kehilangan akses ke warisan budaya dan sejarah yang turut membentuk identitas mereka. Tanah yang dihuni turun-temurun bukan sekadar lahan, tetapi juga simbol cerita, tradisi, dan nilai-nilai yang telah ditanamkan dari generasi ke generasi. Kehilangan akses ke warisan ini dapat mengakibatkan perasaan teralienasi dan hilangnya rasa memiliki terhadap sejarah dan budaya komunitas mereka.
Selain itu, dislokasi seringkali mengakibatkan gangguan pada pendidikan anak-anak dan remaja. Sekolah yang biasa mereka datangi mungkin harus ditutup atau menjadi sulit diakses. Ini, pada gilirannya, dapat mengurangi kualitas pendidikan yang mereka terima dan membatasi peluang mereka di masa depan.
Terakhir, dislokasi juga berdampak pada peluang ekonomi. Generasi muda yang sebelumnya mungkin memiliki peluang bekerja atau berwirausaha di tanah mereka kini harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang mungkin tidak menyediakan peluang yang sama. Hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di antara anggota komunitas dan menciptakan rasa ketidakpastian bagi masa depan generasi muda.
Dengan demikian, meskipun pembangunan mungkin membawa sejumlah manfaat ekonomi, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kultural yang mungkin timbul, terutama bagi generasi muda yang berada di garis depan perubahan tersebut.

Refleksi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan bukan sekedar konsep yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas. Pada kasus Pulau Rempang, tampak bahwa pembangunan proyek Rempang Eco-City menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak komunitas setempat, terutama hak-hak perempuan dan anak.
Refleksi dari situasi ini menunjukkan bahwa pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang tanah, sumber daya, dan warisan budaya mereka. Mengabaikan suara-suara ini bisa mengakibatkan konsekuensi negatif jangka panjang, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi.
Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok atau investor. Ketika perempuan dan anak-anak dikesampingkan dari proses pembangunan, potensi penuh dari komunitas tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam konteks Pulau Rempang, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, mengabaikan aspirasi dan kebutuhan mereka berarti melewatkan kesempatan untuk menciptakan pembangunan yang lebih holistik dan inklusif.
Akhirnya, refleksi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang infrastruktur fisik atau pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ini tentang menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis masyarakat perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan yang sejati.
Bersambung Bagian 5…